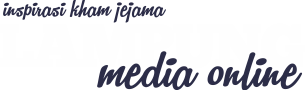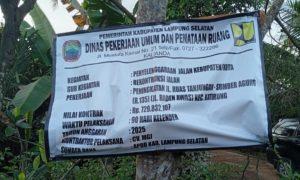Penulis: Anisa Dwi Cahya, Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S. Hut., M. P., IPM
Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Pulau Sumatera, dengan hamparan hutan tropisnya yang dulunya membentang hijau bagaikan
permadani, kini menyimpan bara konflik tenurial yang tak kunjung padam. Alih-alih menjadi
sumber kemakmuran dan keseimbangan ekologis, hutan Sumatera justru menjadi arena
pertarungan kepentingan antara masyarakat adat, perusahaan korporasi, dan negara. Konflik
ini bukan sekadar sengketa lahan, melainkan juga pertempuran atas identitas, hak asasi
manusia, dan masa depan lingkungan. Akar permasalahan yang kompleks, tumpang tindih
regulasi, dan lemahnya penegakan hukum menjadi bahan bakar yang terus menyulut api
sengketa, meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat lokal dan mengancam kelestarian
hutan yang tersisa.
Salah satu akar utama konflik tenurial di Sumatera adalah ketidakjelasan dan tumpang tindih
hak atas tanah dan hutan. Secara historis, masyarakat adat telah mendiami dan mengelola
hutan Sumatera secara turun-temurun dengan sistem kearifan lokal yang terbukti menjaga
keseimbangan ekosistem. Namun, kehadiran negara dengan berbagai kebijakan kehutanan
dan perkebunan, seringkali tanpa pengakuan yang memadai terhadap hak-hak tradisional ini,
menciptakan jurang pemisah yang lebar. Konsesi hutan dan izin perkebunan skala besar yang
diberikan kepada perusahaan seringkali tumpang tindih dengan wilayah adat, memicu
penggusuran, perusakan lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.
Dominasi model pembangunan ekonomi ekstraktif juga menjadi pemicu utama konflik.
Kebutuhan global akan komoditas seperti kelapa sawit, pulp dan kertas, serta pertambangan
mendorong ekspansi industri-industri ini secara masif di Sumatera. Pemerintah, dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seringkali memberikan kemudahan perizinan tanpa
mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Akibatnya, hutan alam
yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat dan penyangga ekologis pulau ini terus
menyusut dan terdegradasi.
Konflik muncul ketika masyarakat adat mempertahankan hak
atas tanah dan sumber daya alam mereka dari klaim perusahaan yang didukung oleh negara.
Lemahnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat memperparah situasi
konflik. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak-hak masyarakat hukum adat,
implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Proses pengakuan wilayah adat
seringkali berbelit-belit, memakan waktu lama, dan rentan terhadap intervensi kepentingan
ekonomi. Ketiadaan peta wilayah adat yang definitif dan diakui secara hukum semakin
mempersulit posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka ketika
berhadapan dengan klaim perusahaan atau kebijakan pemerintah.
Ketidakadilan dalam proses perizinan dan kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi
sumber konflik yang signifikan. Keputusan-keputusan terkait alokasi lahan dan pemberian
izin seringkali diambil secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat lokal secara bermakna.
Masyarakat adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi lingkungan dan
potensi dampak sosial seringkali diabaikan dalam proses konsultasi. Akibatnya, proyek-
proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat justru
memicu perlawanan dan konflik berkepanjangan.
Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten semakin memperkeruh suasana.
Perusahaan yang melanggar aturan, melakukan perusakan lingkungan, atau mengabaikan
hak-hak masyarakat adat seringkali tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Impunitas ini
mendorong perusahaan untuk terus melakukan praktik-praktik yang merugikan, sementara
masyarakat adat merasa tidak memiliki keadilan dan perlindungan dari negara. Korupsi dan
praktik suap dalam proses perizinan dan penegakan hukum juga menjadi hambatan besar
dalam penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan.
Dampak dari konflik tenurial hutan di Sumatera sangat luas dan multidimensional. Dari segi
sosial, konflik ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat adat yang
bergantung pada hutan, terganggunya struktur sosial dan budaya, meningkatnya kemiskinan,
serta terjadinya kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan hak-
haknya. Trauma psikologis akibat penggusuran dan kehilangan identitas juga menjadi luka
mendalam yang sulit disembuhkan.
Dari segi lingkungan, konflik tenurial berkontribusi signifikan terhadap deforestasi dan
degradasi hutan di Sumatera. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan,
seringkali dilakukan secara ilegal atau tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan,
menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, banjir, dan perubahan iklim.
Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia dan penyangga kehidupan, justru menjadi
sumber bencana ekologis.
Dari segi ekonomi, meskipun pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun seringkali tidak
memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Keuntungan yang
besar justru dinikmati oleh segelintir korporasi, sementara masyarakat adat dan petani kecil
justru terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi tumpuan
hidup mereka. Konflik tenurial juga menciptakan ketidakpastian investasi dan menghambat
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mengatasi konflik tenurial hutan di Sumatera secara komprehensif dan berkelanjutan,
diperlukan reformasi tata kelola hutan dan agraria yang mendasar. Langkah-langkah
mendesak yang perlu diambil antara lain:
1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara tegas dan menyeluruh.
Pemerintah perlu mempercepat proses pengakuan wilayah adat melalui peraturan
perundang-undangan yang jelas dan implementatif. Pemetaan partisipatif wilayah adat
harus menjadi prioritas, dan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya
alam di dalamnya harus dihormati dan dilindungi.
2. Peninjauan kembali dan penertiban izin-izin konsesi yang tumpang tindih dengan
wilayah adat dan kawasan hutan yang dilindungi. Proses perizinan harus transparan,
partisipatif, dan akuntabel, dengan melibatkan masyarakat lokal dan
mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara komprehensif. Izin-izin
yang terbukti bermasalah harus dicabut atau direvisi.
3. Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor kehutanan dan
perkebunan. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang melakukan
perusakan lingkungan, penggusuran ilegal, atau mengabaikan hak-hak masyarakat
adat. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.
Mengabaikan konflik tenurial hutan di Sumatera sama dengan membiarkan bom waktu terus
berdetak. Dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang ditimbulkan akan semakin parah
dan sulit dipulihkan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab
bersama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, demi menjaga kelestarian hutan
Sumatera dan menjamin kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya. Sumatera tidak
seharusnya terus “membara” dalam konflik, melainkan kembali menghijau dan memberikan
kehidupan bagi semua.
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat